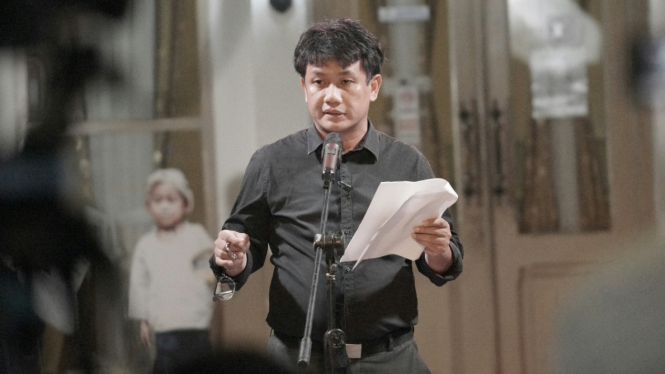VIVA - Indonesia sedang menghadapi tantangan besar yang jarang menjadi headline sehari-hari, tetapi dampaknya terasa di setiap jengkal tanah: degradasi lahan. Sering kali kita sibuk membicarakan isu politik, kriminal, bahkan gosip artis, sementara kerusakan lahan berlangsung senyap dan perlahan merampas daya hidup bangsa ini. Pertanyaannya sederhana tapi krusial: pentingkah restorasi lahan di Indonesia? Atau kita biarkan saja tanah kita lelah, lalu menanggung konsekuensinya di masa depan?
Jika kita menengok laporan terbaru PBB pada peringatan Desertification and Drought Day 2025 di Bogotá, Kolombia, dunia diingatkan bahwa 1,5 miliar hektare lahan perlu direstorasi sebelum 2030 untuk mencegah krisis pangan, air, dan ekonomi yang semakin dalam. Angka itu bukan sekadar statistik global, melainkan peringatan keras yang relevan untuk Indonesia. Negara ini masih menyimpan cadangan lahan luas, tetapi setiap tahun kita kehilangan ribuan hektare karena deforestasi, pertambangan, perkebunan yang tidak terkendali, dan kebakaran hutan. Jika dunia kehilangan 880 miliar dolar per tahun akibat degradasi lahan, bayangkan berapa besar kerugian Indonesia yang hidupnya bertumpu pada tanah, hutan, dan pertanian.
Kasus terbaru di Tanah Air memperlihatkan potret buram yang seharusnya membuat kita semua terjaga. Di Kalimantan Tengah, ribuan hektare lahan gambut yang dulu menjadi paru-paru dunia kini berubah menjadi hamparan tanah tandus dan bekas parit kanal yang kering. Upaya membangun food estate yang digadang-gadang sebagai solusi krisis pangan malah menyisakan tanah kritis yang sulit dipulihkan. Di Sumatera Selatan, kebakaran hutan yang terjadi beberapa bulan lalu membuat ribuan warga terpapar asap pekat. Lahan gambut yang seharusnya menjadi penyimpan air dan karbon kini rapuh, mudah terbakar, dan nyaris kehilangan fungsi ekologisnya. Sementara di Pulau Bangka, lahan-lahan bekas tambang timah menjelma menjadi kawah raksasa berair asam, mengubah lanskap menjadi mirip gurun kecil di tengah pulau tropis.
Fenomena-fenomena ini menegaskan bahwa degradasi lahan bukan hanya terjadi di Afrika atau Timur Tengah. Indonesia pun sedang berjalan di jalur yang sama. Padahal, negeri ini pernah dikenal sebagai lumbung kekayaan hayati yang melimpah. Jika lahan terus rusak tanpa upaya serius restorasi, kita akan menghadapi masalah berlapis: produksi pangan anjlok, bencana ekologis meningkat, dan biaya sosial-ekonomi melonjak tak terkendali.
Mengapa restorasi penting? Karena lahan adalah fondasi dari hampir semua aspek kehidupan. Dari tanah lahir padi, jagung, kedelai, kopi, sawit, hingga rempah-rempah yang menopang ekonomi kita. Dari tanah pula lahir air yang disimpan oleh gambut dan hutan, lalu dialirkan ke sungai-sungai besar. Dari tanah juga kita membangun kota dan infrastruktur yang menopang peradaban. Tanpa tanah yang sehat, tidak ada ketahanan pangan, tidak ada air bersih, dan tidak ada masa depan.
Namun restorasi lahan bukan sekadar urusan teknis menanam pohon atau membuat embung. Restorasi adalah proses panjang yang memerlukan strategi, konsistensi, dan kemauan politik yang kuat. Sayangnya, di Indonesia, proyek-proyek restorasi kerap terjebak dalam logika proyek jangka pendek. Ada lahan bekas tambang direklamasi hanya sebatas formalitas administratif, ditanami bibit seadanya, lalu dibiarkan mati tanpa perawatan. Ada pula proyek penghijauan yang lebih banyak berfungsi sebagai pencitraan ketimbang benar-benar memulihkan ekosistem.
Bandingkan dengan apa yang dilakukan di beberapa belahan dunia. Di Australia, para petani mulai mengadopsi praktik pertanian regeneratif untuk memulihkan kesuburan tanah yang kian rapuh akibat perubahan iklim. Di Afrika, inisiatif Peace Forest bahkan menggabungkan restorasi dengan upaya merajut perdamaian lintas batas. Sedangkan di Eropa, meski masih fragmentaris, setidaknya ada keseriusan untuk membangun observatorium kekeringan agar respons kebijakan lebih terukur. Indonesia tidak bisa terus-menerus menutup mata dengan dalih kondisi berbeda. Justru karena berbeda, kita punya tanggung jawab lebih besar untuk berinovasi sesuai konteks lokal.
Contoh inspiratif sebenarnya ada di negeri ini. Di Jawa Tengah, beberapa desa berhasil menghidupkan kembali lahan kritis dengan sistem agroforestri yang memadukan tanaman keras dengan palawija. Warga tidak hanya mendapatkan kembali kesuburan tanah, tetapi juga tambahan penghasilan dari hasil hutan bukan kayu. Di Kalimantan Barat, upaya restorasi gambut melalui sekat kanal mulai menunjukkan hasil positif, membuat lahan yang semula rawan terbakar kembali basah dan produktif untuk tanaman lokal. Di Lombok, lahan kering berhasil dipulihkan dengan pendekatan sumur resapan dan teknologi sederhana yang berbasis kearifan lokal. Kisah-kisah kecil ini membuktikan bahwa restorasi bukan utopia. Restorasi bisa dilakukan, asalkan ada kemauan dan keberlanjutan.
Namun, mari kita jujur. Restorasi tidak murah. PBB memperkirakan dibutuhkan investasi 1 miliar dolar per hari di tingkat global hingga 2030. Di Indonesia, kebutuhan dananya tentu tidak kecil. Tetapi mari kita bandingkan dengan biaya kerugian akibat degradasi. Kebakaran hutan dan lahan tahun 2019 saja menimbulkan kerugian lebih dari Rp75 triliun, belum termasuk dampak kesehatan dan sosial. Jadi, pertanyaannya bukan lagi apakah restorasi mahal atau tidak, melainkan lebih rela membayar untuk memperbaiki atau untuk menanggung kerusakan.
Restorasi lahan juga bukan sekadar tanggung jawab negara. Sektor swasta yang selama ini menikmati keuntungan dari eksploitasi lahan harus ikut menanggung beban. Perusahaan tambang, perkebunan, dan properti tidak bisa lagi bersembunyi di balik program CSR yang hanya berupa pembagian bibit atau acara tanam pohon seremonial. Mereka harus terlibat dalam restorasi yang nyata, dengan indikator keberhasilan yang bisa diukur, diawasi, dan dipertanggungjawabkan. Di sisi lain, masyarakat lokal harus diberi ruang dan kapasitas untuk menjadi pelaku utama restorasi, bukan sekadar penonton. Sebab, mereka yang paling merasakan dampak degradasi sekaligus yang paling paham dengan kearifan lokal untuk memulihkan tanahnya.
Jika restorasi gagal menjadi agenda nasional, Indonesia akan masuk dalam jebakan krisis berlapis. Pertama, krisis pangan akibat menurunnya produktivitas lahan pertanian. Kedua, krisis air bersih karena daerah resapan hilang. Ketiga, krisis kesehatan karena polusi asap kebakaran terus berulang. Keempat, krisis sosial-ekonomi karena masyarakat desa kehilangan sumber penghidupan, lalu bermigrasi ke kota yang sudah penuh sesak.
Karena itu, restorasi lahan bukan lagi pilihan, melainkan keharusan. Pertanyaannya, apakah kita mau melakukannya dengan serius atau sekadar ikut arus seremonial global? Indonesia punya peluang besar untuk menjadi contoh dunia. Dengan luas lahan, keragaman ekosistem, dan budaya gotong royong yang masih hidup, kita sebenarnya memiliki modal sosial-ekologis yang kuat. Yang kita butuhkan adalah keberanian politik untuk memprioritaskan masa depan dibandingkan keuntungan sesaat.
Peringatan Desertification and Drought Day 2025 seharusnya menjadi momentum bagi Indonesia untuk mengubah cara pandang. Restorasi bukan proyek sampingan, melainkan inti dari pembangunan berkelanjutan. Jika kita terus menunda, tanah akan menagih balasannya dalam bentuk bencana dan krisis yang lebih besar. Tetapi jika kita berani melangkah sekarang, tanah yang kita pulihkan akan menjadi warisan paling berharga bagi generasi mendatang.
Jadi, pentingkah restorasi lahan di Indonesia? Jawabannya jelas, sangat penting, bahkan lebih penting daripada sekadar menggenapi target internasional. Ini soal bertahan hidup sebagai bangsa. Tanpa tanah yang sehat, tidak ada Indonesia yang kokoh. Restorasi adalah jalan panjang, tetapi setiap langkah kecil hari ini akan menentukan arah masa depan. Pilihan ada di tangan kita, merawat atau kehilangan.
Halaman Selanjutnya
Contoh inspiratif sebenarnya ada di negeri ini. Di Jawa Tengah, beberapa desa berhasil menghidupkan kembali lahan kritis dengan sistem agroforestri yang memadukan tanaman keras dengan palawija. Warga tidak hanya mendapatkan kembali kesuburan tanah, tetapi juga tambahan penghasilan dari hasil hutan bukan kayu. Di Kalimantan Barat, upaya restorasi gambut melalui sekat kanal mulai menunjukkan hasil positif, membuat lahan yang semula rawan terbakar kembali basah dan produktif untuk tanaman lokal. Di Lombok, lahan kering berhasil dipulihkan dengan pendekatan sumur resapan dan teknologi sederhana yang berbasis kearifan lokal. Kisah-kisah kecil ini membuktikan bahwa restorasi bukan utopia. Restorasi bisa dilakukan, asalkan ada kemauan dan keberlanjutan.
Disclaimer: Artikel ini adalah kiriman dari pengguna VIVA.co.id yang diposting di kanal VStory yang berbasis user generate content (UGC). Semua isi tulisan dan konten di dalamnya sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis atau pengguna.

 3 weeks ago
10
3 weeks ago
10