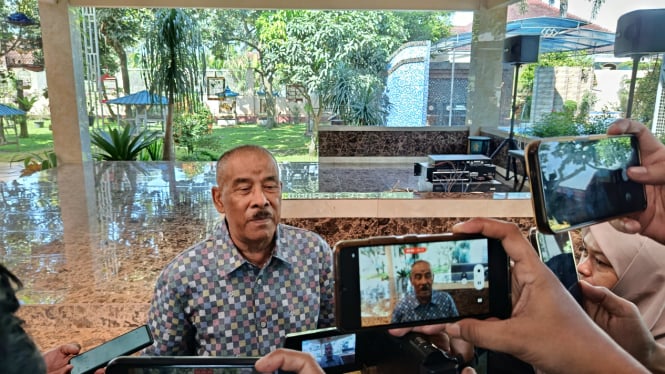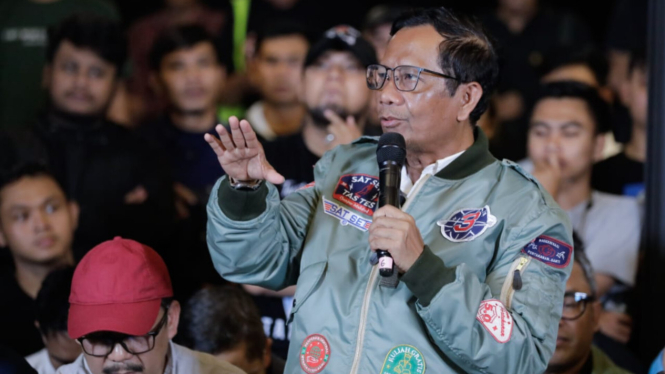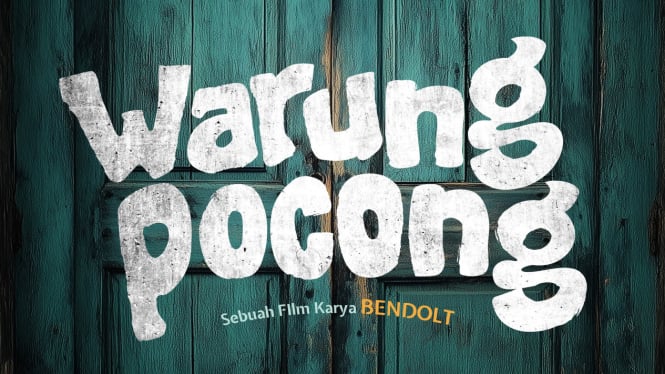VIVA – Banyak pejabat yang mempersilakan publik untuk menggugat UU TNI jika tak setuju dengan revisi UU TNI. Salah satunya adalah Menteri Hukum yang mempersilakan masyarakat mengajukan judicial review terhadap UU TNI ke Mahkamah Konstitusi (MK). Hal ini mencerminkan fenomena klasik dalam politik legislasi kita: lempar tanggung jawab. Seakan-akan, jika ada ketidakpuasan terhadap suatu undang-undang, solusinya semata-mata adalah menguji konstitusionalitasnya di MK. Padahal, proses pembentukan undang-undang adalah hasil perundingan antara pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat, bukan ranah MK.
Fenomena ini bukan hal baru. Setiap kali ada undang-undang kontroversial, pejabat publik sering kali berdalih bahwa masyarakat dapat menggugatnya melalui MK, alih-alih mengakui adanya “cacat” dalam proses legislasi. Hal ini bukan cuma menunjukkan lemahnya komitmen terhadap proses deliberatif yang partisipatif, tetapi juga menumpuk beban ke MK yang sejatinya bukan tempat bagi pemerintah dan DPR untuk "membuang" produk legislasi yang bermasalah.
Politik Legislasi yang Bermasalah
Pengesahan revisi UU TNI yang dilakukan secara “serampangan” dan “ugal-ugalan” telah menimbulkan keresahan di masyarakat. Salah satu aspek krusial yang menjadi sorotan adalah kemungkinan semakin dominannya peran militer dalam ranah sipil, yang berpotensi merusak prinsip supremasi sipil dan demokrasi. Penolakan publik yang luas terhadap revisi UU TNI menunjukkan bahwa ada persoalan serius dalam proses pembentukan regulasi ini, baik dari sisi substansi maupun partisipasi publik. Selain pada revisi UU TNI, hal serupa terjadi juga pada revisi UU KPK, UU Minerba, UU Cipta Kerja, dan UU IKN.
Kendati demikian, alih-alih melakukan koreksi terhadap proses legislasi yang bermasalah, pemerintah justru mengalihkan tanggung jawab ke MK. Padahal, jika sejak awal DPR dan pemerintah melibatkan masyarakat secara lebih luas dalam proses penyusunan undang-undang, polemik ini bisa diminimalisasi.
Judicial review ke MK sejatinya bukanlah mekanisme untuk menutupi kelemahan dalam proses legislasi yang tidak demokratis dan minim transparansi. Di sinilah letak permasalahan utama: ketidakseriusan pemerintah-DPR dalam memastikan legislasi yang berkualitas. Banyak undang-undang disusun tanpa partisipasi yang berarti, diwarnai oleh transaksi politik, dan minim kajian akademik yang mendalam. Dalam kondisi ini, MK kemudian dipaksa untuk menjadi "pemungkas" dari semua kesalahan legislasi, sebuah peran yang sejatinya tidak sesuai dengan tugas utamanya sebagai pengawal konstitusi.
MK Bukan Tempat Sampah Legislasi
MK sejatinya dibentuk sebagai pengawal konstitusi, bukan sebagai tempat untuk membuang undang-undang yang “cacat” secara prosedural maupun substansial. Dalam pelbagai kasus, MK memang berperan penting dalam mengoreksi undang-undang yang bertentangan dengan UUD NRI 1945. Namun, jika mekanisme judicial review terus-menerus dijadikan jalan keluar dari buruknya legislasi di DPR dan pemerintah, maka ini hanya akan memperburuk keadaan.
MK memiliki keterbatasan dalam mengubah substansi suatu undang-undang. Judicial review cuma bisa membatalkan atau menyatakan norma tertentu inkonstitusional, tetapi tidak serta-merta dapat memperbaiki ketimpangan yang ada dalam desain regulasi secara menyeluruh—meskipun dalam perkembangannya, MK sering kali berperan tidak cuma sebagai negative legislature, melainkan juga positive legislature (Martitah, 2023).
Pembuatan undang-undang semestinya menjadi ranah utama DPR-pemerintah, bukan MK. Legislasi idealnya dibentuk melalui mekanisme deliberatif dengan partisipasi publik yang bermakna—bukan sekadar formalitas. Meskipun sering dimanipulasi atau diabaikan, keterlibatan masyarakat dalam tahap awal legislasi lebih efektif dalam mencegah regulasi bermasalah dibandingkan judicial review yang hanya menguji konstitusionalitas norma setelah UU disahkan.
Jika DPR-pemerintah serius memastikan kualitas legislasi, partisipasi publik tidak boleh dianggap hambatan, melainkan bagian dari proses demokratis esensial. Tanpa itu, legislasi cuma menjadi alat transaksional politik, dan MK terus dijadikan tempat sampah untuk menampung UU bermasalah, bertentangan dengan prinsip negara hukum dan demokrasi konstitusional.
Maka, membebankan harapan perubahan melalui judicial review adalah sebuah ilusi yang menyesatkan. Lebih dari itu, menjadikan MK sebagai solusi atas legislasi yang buruk pun berpotensi melemahkan kredibilitas lembaga ini. Beban perkara yang terus meningkat akibat buruknya legislasi dapat menghambat MK dalam menjalankan fungsi utamanya secara optimal. Jika kondisi ini terus berlanjut, kita tidak cuma akan menyaksikan degradasi kualitas legislasi, tetapi juga erosi terhadap kewibawaan MK sebagai institusi yang berfungsi menjaga konstitusi.
Reformasi Legislasi yang Berorientasi pada Partisipasi Publik yang Bermakna
Sudah saatnya DPR-pemerintah serius dalam membenahi proses pembentukan undang-undang. Prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik harus menjadi fondasi utama dalam setiap penyusunan regulasi. Undang-undang yang baik bukanlah produk yang mesti terus-menerus diuji di MK, melainkan hasil dari proses legislasi yang inklusif dan berbasis pada kepentingan publik.
Mengandalkan judicial review sebagai satu-satunya solusi untuk memperbaiki regulasi yang bermasalah adalah bentuk pengabaian terhadap tanggung jawab legislasi yang demokratis. Jika kondisi ini terus berlanjut, maka kita akan semakin terjebak dalam siklus pembuatan kebijakan yang tidak hanya cacat secara prosedural, tetapi juga merusak fondasi negara hukum yang kita bangun.
Permasalahan legislasi di Indonesia berulang dari hulu ke hilir: inisiatif undang-undang lahir dari kepentingan elite, pembahasan di DPR sarat kompromi politik, dan judicial review di MK menjadi koreksi terakhir. MK sejatinya bukanlah tempat sampah bagi undang-undang yang disusun secara serampangan. Pemerintah-DPR wajib berhenti memperlakukan MK sebagai solusi instan bagi masalah legislasi mereka sendiri. Jika mereka serius dalam membangun negara hukum yang demokratis, maka semestinya mereka mulai dari pembenahan proses legislasi yang lebih transparan dan partisipatif.
Pola semacam ini mencerminkan kegagalan fundamental dalam politik legislasi Indonesia, yang mana hukum lebih sering lahir sebagai hasil kompromi kepentingan elitis ketimbang cerminan aspirasi rakyat. Jika DPR-pemerintah terus mengabaikan prinsip deliberatif dan transparansi dalam pembentukan undang-undang, maka legitimasi hukum yang dihasilkan akan selalu dipertanyakan, menciptakan lingkaran setan ketidakpercayaan publik terhadap institusi demokrasi.
Dalam jangka panjang, praktik ini tidak hanya merusak fondasi negara hukum, tetapi juga memperkuat oligarki yang menjadikan legislasi sebagai instrumen dominasi politik dan ekonomi segelintir elite, alih-alih alat untuk menegakkan keadilan dan kesejahteraan bersama. Reformasi menyeluruh diperlukan, mulai dari memperkuat kajian akademik dan partisipasi publik yang bermakna, memastikan transparansi di DPR, hingga mengurangi ketergantungan pada MK. Tanpa perubahan ini, negara hukum yang demokratis akan tetap rapuh.
Halaman Selanjutnya
Jika DPR-pemerintah serius memastikan kualitas legislasi, partisipasi publik tidak boleh dianggap hambatan, melainkan bagian dari proses demokratis esensial. Tanpa itu, legislasi cuma menjadi alat transaksional politik, dan MK terus dijadikan tempat sampah untuk menampung UU bermasalah, bertentangan dengan prinsip negara hukum dan demokrasi konstitusional.
Disclaimer: Artikel ini adalah kiriman dari pengguna VIVA.co.id yang diposting di kanal VStory yang berbasis user generate content (UGC). Semua isi tulisan dan konten di dalamnya sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis atau pengguna.

 3 weeks ago
10
3 weeks ago
10